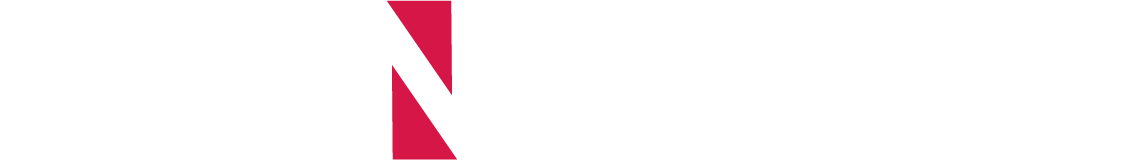THINKWAY.ID – Di hari Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah), umat Islam yang mampu secara materi, diperintahkan untuk menunaikan ibadah qurban. Hal ini ditegaskan al-Qur’an surat al-Kautsar ayat 1 dan 2:
إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر…
“Sungguh Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak, maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, lalu berqurbanlah (sebagai ibadah serta upaya mendekatkan diri kepada Allah)… “
Sejarah qurban, sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam AS, yakni ketika kedua putra beliau (Qabil dan Habil) mendapat perintah dari Allah agar berqurban. Sebagai petani, Qabil diperintahkan mengorbankan sebagian hasil taninya, sedangkan Habil dituntut mempersembahkan sebagian hasil ternaknya.
Pada masa Nabi Ibrahim AS dan sebelumnya, manusia sering kali menjadikan sesama manusia sebagai korban (sesajen) kepada tuhan-tuhan atau dewa-dewa yang mereka sembah. Di Mesir misalnya, gadis tercantik dipersembahkan kepada Dewi Sungai Nil. Di Kanaan, Irak, bayi-bayi dipersembahkan kepada Dewa Baal. Di Mexico, suku Aztec menyerahkan jantung dan darah manusia kepada Dewa matahari. Sementara di Eropa Utara, orang-orang Viking mengorbankan pemuka-pemuka agama mereka kepada Dewa Perang “Odin”.
Nabi Ibrahim AS hidup pada abad ke-18 SM, suatu masa ketika terjadi persimpangan jalan pemikiran kemanusiaan tentang korban-korban yang masih berwujud manusia. Di satu pihak ada yang mempertahankan tradisi mengorbankan manusia, dan di pihak lain ada yang beranggapan bahwa manusia terlalu mulia untuk dikorbankan. Di sinilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS memberi jalan keluar yang memuaskan semua pihak. Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah SWT melalui mimpi yang benar (ru’yah shadiqah) untuk menyembelih anak kesayangannya (Ismail AS), sebagai isyarat bahwa anak tercinta, dambaan hati belahan jiwa bukanlah sesuatu yang berarti jika Yang Maka Kuasa telah meminta.
Namun demikian, bukan berarti mempertahankan tradisi pengorbanan, karena setelah pisau dihunjamkan dan digerakkan untuk menyembelih sang anak sebagai korban, tiba-tiba seekor kambing kibas dijadikan penggantinya. Hal ini sekaligus memberi isyarat bahwa Allah sedemikian kasih kepada manusia, sehingga tidak diperkenankan adanya korban manusia. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim AS yang puncaknya dirayakan sebagai ‘Idul Adha, harus mampu mengingatkan bahwa yang dikorbankan tidak boleh manusia, melainkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti rakus, menindas, menyerang, barbar (tidak mengenal hukum serta norma-norma susila), ambisi buta, licik, zhalim dan sejenisnya. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus ditiadakan, dan dijadikan korban demi mencapai kedekatan diri kepada Allah SWT.
Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, Juz 3, h. 274 merumuskan pengertian qurban (udhhiyah):
إسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى
“Nama untuk jenis hewan ternak, baik berupa unta, sapi, dan kambing yang disembelih di hari ‘Idul Adha dan hari-hari Tasyrik sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.”
Hukum berqurban adalah sunnah muakkadah, tetapi khusus untuk Rasulullah saw hukumnya wajib. Hal ini didasarkan penegasan sebuah hadis riwayat at-Tirmidzi:
أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ “Aku diperintahkan (diwajibkan) untuk berqurban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian” (Riwayat at-Tirmidzi).
Kesunnahan dalam konteks hadis tersebut adalah sunnah kifayah, yakni jika dalam keluarga ada satu dari anggota keluarga yang telah menjalankan qurban, maka gugurlah kesunnahan yang lain, tetapi jika hanya satu orang, maka hukumnya adalah sunnah ‘ain. Sedang kesunnahan berqurban ini tentunya ditujukan kepada orang muslim yang merdeka, sudah baligh, berakal, dan mampu.
وَالْاُضْحِيَة- ….(سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَاعَلَى الْكِفَايَةِ إِنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِذَا فَعَلَهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ كَفَى عَنِ الْجَمِيعِ وَإِلَّا فَسُنَّةُ عَيْنٍ وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْمُسْلِمُ اَلْحُرُّ اَلْبَالِغُ اَلْعَاقِلُ اَلْمُسْتَطِيعُ
“Hukum berqurban adalah sunnah muakkadah yang bersifat kifayah. Apabila jumlahnya dalam satu keluarga itu banyak, dan salah satu dari mereka sudah menjalankan qurban, maka sudah mencukupi untuk semuanya. Jika tidak, maka menjadi sunnah ‘ain. Sedangkan mukhatab (orang yang terkena khitab) adalah orang Islam yang merdeka, sudah baligh, berakal dan mampu” (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi asy-Syuja’, Bairut: Maktab al-Buhuts wa ad-Dirasat, tth, Juz. 2, h. 588).
Jumhur ulama sepakat mengenai kedudukan hukum qurban, yaitu sunnah muakkadah kifayah. Namun muncul persoalan tentang berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Biasanya hal ini dilalukan oleh pihak keluarganya, karena orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup belum pernah berqurban. Syeikh Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam kitab Minhaj ath-Thalibin dengan tegas menyatakan, tidak ada qurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali semasa hidupnya pernah berwasiat. Ia menjelaskan:
وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا “Tidak sah berqurban untuk orang lain (yang masih hidup) dengan tanpa seizinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk diqurbani” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-1, 1425 H/2005 M, h. 321).
Setidaknya, argumentasi yang dapat dikemukakan untuk menopang pendapat ini adalah bahwa qurban merupakan ibadah yang membutuhkan niat. Karenanya, niat orang yang berqurban mutlak diperlukan. Tetapi ada pandangan lain yang menyatakan kebolehan berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu al-Hasan al-Abbadi, yang beralasan bahwa berqurban termasuk sedekah, sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan dapat memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya dapat sampai kepadanya, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.
لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِإذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ (وَأَمَّا) التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُوالْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُ هُوَتَصِلُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ
“Seandainya seseorang berqurban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka tidak boleh. Adapun berqurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, Abu al-Hasan al-Abbadi memperbolehkannya secara mutlak, karena termasuk sedekah, sedangkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya, dan pahalanya dapat sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma’ ulama” ( Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Beirut-Dar al-Fikr, tth, Juz 8, h. 406).
Berqurban untuk Orang yang Sudah Meninggal
Analogi qurban dengan sedekah didasarkan pada penjelasan beberapa hadis. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas ra, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw: “sungguh ibuku telah wafat, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Jawab Rasul: ya. Orang itu berkata: sungguh aku mempunyai kebun yang berbuah, karena itu aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku telah menyedekahkannya atas nama ibuku” (Riwayat Bukhari).
Dalam hadis lain disebutkan, dari Abu Hurairah ra, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, “sungguh ayahku telah meninggal dan tidak meninggalkan pesan. Apakah bermanfaat baginya bila aku bersedekah? Rasul menjawab: ya” (Riwayat Muslim).
Dari kedua hadis ini, dapat dilihat bahwa sedekah boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, khususnya atas nama orang tua. Adapun pahalanya, akan sampai kepada mereka walau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Atas dasar inilah, Abu al-Hasan al-Abbadi membolehkan berqurban untuk orang yang telah meninggal, walaupun tidak ada wasiat di masa hidupnya.
Di kalangan madzhab Syafi’i, pandangan yang menyatakan tidak sah berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih (ashah), dan dianut mayoritas ulama dari kalangan madzhab syafi’i.
Al-Imam Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy al-Hashaniy al-Dimasyqiy al-Syafi’iy dalam kitab Kifayat al-Akhyar juz 2, h. 236 menyatakan: ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها (Tidak boleh berqurban untuk orang yang sudah meninggal dunia menurut pendapat yang paling shahih, kecuali jika ia semasa hidupnya berwasiat).
Kendati pandangan yang membolehkan berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia tidak menjadi pandangan mayoritas ulama mazhab syafi’i, namun pandangan ini didukung oleh madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dijelaskan:
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضْحِيَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالاِتِّفَاقِ. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ إِنْفَاذُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَافَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لاَ يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ
“Apabila (orang yang telah meninggal dunia) belum pernah berwasiat untuk diqurbani, kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka madzhab Hanafi, maliki, dan Hanbali memperbolehkannya. Hanya saja, menurut madzhab maliki, walaupun boleh tetapi makruh.
Alasan mereka adalah karena kematian tidak dapat menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertaqarrub kepada Allah, sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji” (Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah-Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, Beirut: Dar as-Salasil, Juz, 5, h. 106-107).
Intinya, jadikan perbedaan pandangan para ulama dalam masalah fiqh sebagai rahmat. Umar bin ‘Abd al-‘Aziz berkata: “ikhtilafu ummati rahmah” (perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat). Jika ingin berqurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia, maka berarti mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, yaitu Abu al-Hasan al-‘Abbadi, madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Bersikap dewasa dalam memahami perbedaan yang bersifat ijtihadiyah merupakan langkah konstruktif yang dianjurkan agama.
Kaidah ushul fiqh menyebutkan: “khuruj al-khilaf mustahab”. Dalam sebuah hadis riwayat at-Tirmidzi, para pengurban diingatkan agar meluruskan niat dan ikhlas di kala berqurban (… fathibu biha nafsan, bersihkanlah dirimu dengan berqurban).
Referensi
- Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi asy-Syuja’, Bairut: Maktab al-Buhuts wa ad-Dirasat, tth, Juz. 2, h. 588.
- Muhyiddin Syarf an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-1, 1425 H/2005 M, h. 321.
- Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Beirut-Dar al-Fikr, tth, Juz. 8, h. 406.
- Sayid Sabiq, Fiq al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H, Juz 3, h. 274.
- Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy al-Hashaniy al-Dimasyqiy al-Syafi’iy, Kifayat al-Akhyar, Beirut: Dar al-Fikr, tth., Juz 2, h. 236.
- Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah-Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, Beirut: Dar as-Salasil, Juz, 5, h. 106-107.