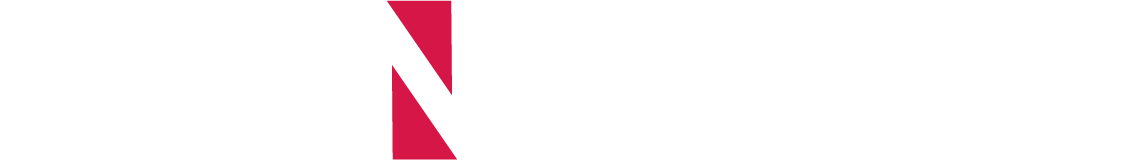THINKWAY.ID – Jika manusia terdahulu mengekspresikan emosinya dalam bentuk teriakan atau lukisan di dinding goa maka kini juga kurang lebih sama. Perbedaannya ada pada mediumnya. Sejak kehadiran media sosial semua kegelisahan, aspirasi, atau apa pun tentang bentuk ekspresi diri menjadi tumpah ruah di sana. Namun, regulasi yang dibangun oleh platform dan negara dirasa membatasi hal tersebut. Masih adakah ruang ekspresi di sosial media?
Tagar black lives matter bisa jadi disebut sebagai tagar dengan aspirasi politik yang paling populer di jagat media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube sekalipun tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan juga turut mempromosikannya agar rasisme hilang dari bumi ini. Berbagai macam ekspresi terkait tagar tersebut memiliki warna yang beragam di sosial media.
Tapi pertanyaannya apakah semua bentuk ekspresi diri diakomodir oleh platform media sosial? Agak naif jika menjawab tersebut dengan kata iya. Mengingat ada batasan-batasan tertentu yang dilarang oleh platform sosial media untuk ditampilkan seperti kekerasan, seks, dan aktivitas yang dianggap tabu oleh norma sosial di sebagian masyarakat tertentu. Batasan-batasan tersebut ternyata tidak hanya dibatasi oleh platform, akan tapi beberapa kali dibatasi pula oleh sebuah negara.
Hal ini kemudian menjadi titik kronis dari media sosial yang berada di ruang digital melampaui batas-batas negara dan dengan penduduk maya didalamnya yang disebut netizen. Pengguna media sosial belum tentu menduplikasi dirinya yang asli seperti di dunia nyata. Bisa jadi kewarganegaraannya diganti atau tak disebut, gendernya disamarkan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika media sosial hadir, muncul asa bahwa manusia bisa hidup tanpa aturan negara dan bisa bebas di sebuah ruang maya.
Tapi nyatanya tidak semudah itu, Ferguso!!! Impian akan adanya kehidupan yang bebas di media sosial terbentur oleh kedaulatan sebuah negara. Di sebuah negara yang dipimpin oleh diktator, ekspresi dalam bentuk kritik, sumpah serapah, meme ejekan kepada pimpinan di daerah tersebut pasti akan mendapatkan sensor dan pelarangan-pelarangan. Pembatasan itu bisa saja melalui regulasi atau yang lainnya.
Oke, jika itu dirasa terlalu berat mari kita coba melihat dari kasus yang sederhana tapi unik, yakni aktivitas merokok. Di Indonesia, regulasi menyebutkan bahwa iklan rokok dalam bentuk apa pun dilarang menampilkan bentuk produk dan aktivitas merokok. Apabila ada yang swafoto dirinya merokok dan ditampilkan di baliho-baliho besar pun bisa saja dilarang karena sarana medium baliho besar memang diperuntukkan untuk iklan dan promosi.
Lantas pertanyaannya bagaimana di media sosial? Secara spesifik belum ditemukan adanya pelarangan aktivitas merokok untuk ditampilkan di media sosial. Namun, Anda tidak boleh untuk mempromosikan produk rokok untuk kepentingan komersil di sosial media. Merujuk pada aturan di Instagram misalnya, disebutkan bahwa “Anda tidak boleh menggunakan layanan Instagram untuk tujuan ilegal atau tidak sah”. Promosi rokok bisa jadi disebutkan sebagai aktivitas ilegal atau tidak sah. Tetapi, sekali lagi bahwa ini hanya tafsiran belaka dan belum mutlak adanya.
Di Indonesia, opini sebagian publik mengingkan negara untuk melarang adanya promosi produk rokok di media sosial. Dorongannya adalah pembentukan regulasi (baik itu membuat regulasi baru atau merevisi yang sudah ada) agar tidak ada lagi iklan rokok di media sosial. Opini ini sepertinya harus disimak secara teliti dan baik-baik. Mengingat, jangan sampai aturan ini dibuat dengan Bahasa yang bias dan tafsirnya abu-abu sehingga tidak merugikan banyak pihak apalagi membatasi ruang ekspresi publik.
Yang ditakutkan adalah ketika aturan itu dibuat maka segala macam aktivitas merokok akan dilarang tampil di sosial media. Padahal belum tentu aktivitas merokok yang ditampilkan tersebut memiliki unsur komersil didalamnya. Nah, hal ini disebut sebagai pembatasan ekspresi di media sosial yang digadang-gadang mampu menjembatani kebutuhan untuk menjadi ruang publik. Jumlah perokok di Indonesia memiliki angka yang besar, akan tetapi agak lucu jika menyebut ekspresi mereka di media sosial dengan foto atau video merokok disebut sedang mempromosikan merek tertentu.
Argumen yang dibangun dari opini pelarangan promosi produk rokok di media sosial adalah upaya menurunkan prevalensi perokok anak. Argumen itu sepertinya tidak ada yang membantah, tapi yang perlu diingat adalah bagaimana meletakkan platform media sosial itu sendiri di masyarakat. Di Instagram misalnya, aturan soal umur ditentukan di sana yaitu anak berusia di bawah 13 tahun belum bisa membuat akun dan bermain di sosial media tersebut. Lantas, jika kemudian ada anak di bawah usia tersebut yang bisa mengaksesnya, kata salah akan kita tuding kemana?
Media sosial sebenarnya bukan rumah yang bebas dimasuki oleh anak-anak. Di Indonesia, data menurut Hootsuite menyebutkan bahwa rentang usia 18-34 tahun adalah yang tertinggi dalam menggunakan sosial media. Asumsinya adalah konten-konten yang tersaji di sana sudah pasti diwarnai dengan konten-konten untuk rentang usia tersebut dan minim bagi anak-anak. Jika anak-anak di bawah usia 18 tahun mengakses media sosial dengan leluasa dan tanpa bimbingan orang tua, ini akan menjadi sebuah masalah. Lalu, bagaimana bisa tudingan prevalensi perokok anak gegara aktivitas merokok di media sosial menjadi landasan utamanya?
Jika opini sebagian publik untuk melarang rokok di media sosial berbasis argumen dengan landasan yang lemah itu diakomodir dalam bentuk regulasi, hal ini justru dapat memicu pembatasan ruang ekspresi di media sosial. Wajar kalau muncul kecurigaan karena seringkali aturan di Indonesia dibuat dengan bahasa dan tafsir yang abu-abu. Jangan sampai iklan rokok akhirnya dilarang, tetapi aktivitas merokok yang sebenarnya bebas dari kepentingan komersil juga ikutan kena. Padahal term of use di media sosial tidak menyebutkan secara spesifik pelarangan-pelarangan itu.