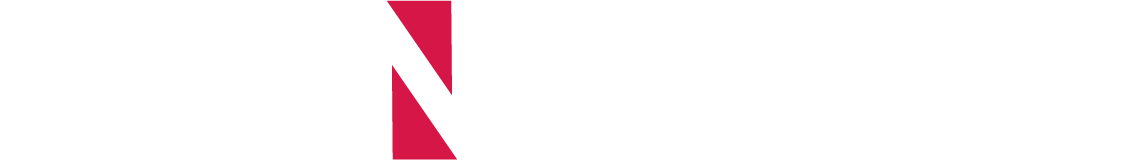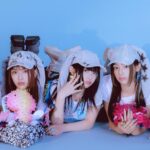THINKWAY.ID – Tahun ini, pemerintah merilis jumlah hari libur nasional sebanyak 24 hari, sangat jauh jika dibandingkan dengan 2022, yang hanya 16 hari libur nasional. Tahun lalu, warganet banyak yang mengeluhkan jumlah yang terhitung sedikit tersebut.
Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 yang disampaikan pada Senin (26/12/2022), dengan rincian 16 hari untuk hari libur nasional, dan 8 tanggal merah untuk cuti bersama.
Jika dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya jumlah ini terhitung banyak. Misalnya untuk negara Swiss saja, tahun ini hanya punya 15 hari libur nasional. Padahal kita mengenal negara-negara Eropa dengan warganya yang seolah dengan mudah bisa traveling ke negara lain dalam waktu yang lebih panjang dan fleksibel.
Lalu apa hubungannya dengan sektor pariwisata dan produktivitas pekerjaan? Tenyata ada, walaupun ukurannya masih bias. Apakah jumlah hari libur nasional serta bisa jadi stress release (melepaskan stress) pada para pekerja dalam konteks yang terjadwal alias harus ngantor? Bisa jadi, tapi sangat tergantung dari sifat pemanfaatan hari libur tersebut.
Mondayisation dan Kejepitnation
Pada Selasa (6/1), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengusulkan dalam cuitannya di Twitter, “hari kejepit” dijadikan hari libur nasional. Ia mengklaim, ini berpotensi jadi katalis positif atau percepatan yang bagus untuk mendongkrak pariwisata terkait pergerakan wisatawan nusantara atau wisnus, wisatawan domestik yang melakukan perjalanan antar kota dengan durasi lebih dari 6 jam.
Harpitnas, istilah slang dari akronim “Hari Kejepit Nasional” dikenal masyarakat dengan pengertian hari kerja yang ada di antara hari libur. Usul Sandi soal ini cukup beralasan, karena langkah serupa juga diterapkan di Selandia Baru dan Singapura.
Di Selandia baru, dikenal istilah Mondayisation, berupa kondisi saat hari libur nasional jatuh pada akhir pekan, maka jatah libur karyawan dapat dipindahkan ke Senin atau Selasa berikutnya. Sandi mengenalkan istilah baru untuk ini, yaitu “Kejepitnation”.
Usulan ini diikuti dengan wacana yang menguntungkan pekerja. Misalnya, kalau liburan nasional jatuh pada akhir pekan, pekerja harus mendapat kompensasi tertentu. Karyawan boleh memilih apakah dibayar gajinya, atau mengambil jatah libur pada Senin, atau pada Jumatnya.
Banyak Libur = Produktif?
Sebuah riset dan eksperimen yang dilakukan Perpetual Guardian, sebuah perusahaan di Selandia Baru, menyebutkan bahwa memperbanyak liburan bisa membuat pekerja lebih produktif. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah menerapkan hari kerja karyawan hanya 4 kali dalam seminggu.
Hasil eksperimen ini menyebutkan, para pekerja jadi lebih kreatif memecahkan masalah. Para karyawan juga semakin tanggap dan ontime dengan tugas ataupun deadline. Semangat kerja menanjak dan menjadi lebih termotivasi mencari cara agar lebih produktif saat bekerja.
Waktu yang berkualitas adalah sasaran utama saat karyawan diberikan waktu liburan lebih banyak. Mereka jadi punya waktu untuk melakukan hobinya, melakukan perawatan diri, dan punya waktu lebih untuk diri sendiri dan keluarga. Amazon, perusahaan raksasa dari Amerika telah mengadopsi cara ini. Karyawan hanya dibebankan waktu bekerja 30 jam selama seminggu.
Kelemahan Kejepitnation
Walaupun demikian, terdapat kelemahan apabila usulan Kejepitnation ini jadi dilegalkan. Jumlah hari dalam liburan beruntun tersebut terhitung pendek, rata-rata maksimal 3-4 hari saja.
University of Tampere di Finlandia pernah melakukan penelitian, yang menyebutkan bahwa manusia hanya butuh 8 hari untuk menikmati liburan dengan maksimal. Syaratnya, 8 hari itu harus berlangsung secara berurutan dan bersambung, untuk memastikan tercapainya kebahagiaan yang mendekati paripurna. Angka ini diperoleh, karena kalau sudah melebihi jumlah hari tersebut, manusia sudah melewati fase jet lag dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Belum lagi, hal ini tak bisa mutlak berlaku untuk para karyawan yang punya target load kerja tinggi, misalnya buruh pabrik yang tak punya opsi lain. Dikhawatirkan akan timbul kesenjangan sosial jika ini mulai efektif diberlakukan.
Bisa jadi hal ini sebenarnya sudah diterapkan dengan mandiri secara perseorangan pada para pekerja di sektor industri kreatif, profesi digital nomad, dan pekerja harian lepas. Ini tak lepas dari sifat pekerjaan para pekerja itu yang bisa “memerintah waktu” sebagai privilege terkait dengan sifat pekerjaaan mereka.