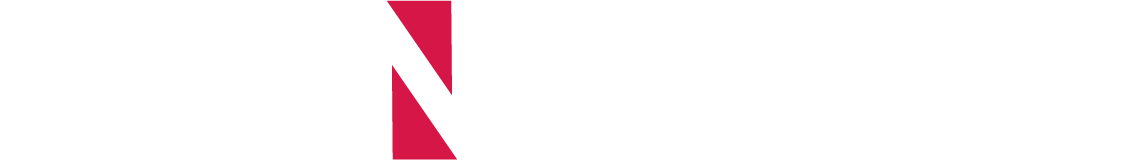Oleh Abdul Jalil (Widyaiswara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
THINKWAY.ID – ‘Idul Fitri bagian integral dari Ramadhan, sebab tidak mungkin ada ‘idul fitri tanpa adanya Ramadhan. Makna Ramadhan hanya dapat dipahami dan dirasakan keberadaannya oleh orang-orang yang menghidupkan Ramadhan dengan ibadah puasa, shalat berjama’ah, shalat tarawih, tadarus al-Qur’an, qiyam al-lail, sedekah, serta amal-amal kebajikan lainnya. Berbeda dengan mereka yang tidak berpuasa, tidak shalat, tidak tarawih, tidak tadarus al-Qur’an, tidak qiyam al-lail, tidak sedekah, dan tidak melakukan amal-amal kebajikan, kehadiran ‘idul fitri hanya dipandang sebagai tradisi tahunan yang identik dengan pakaian baru, mudik lebaran, aneka ragam makanan dan minuman, berkunjung ke handai taulan, serta hingar bingar kesenangan duniawi.
Nasihat bijak mengatakan:
ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد
“Bukanlah berhari raya (‘idul fitri) bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi dikatakan berhari raya (‘idul fitri) bagi orang yang ketaatannya bertambah.”
Seikh Ibrahim al-Baijuri dalam kitab Jauharat al-Tauhid menegaskan:
ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان
“Seseorang dapat dipastikan bertambah imannya, jika ia bertambah ketaatannya kepada Allah SWT.”
Secara harfiah, ‘idul fitri berarti kembali kepada fitrah. Sesuatu yang kembali pada mulanya berada pada suatu keadaan atau tempat, kemudian meninggalkan keadaan atau tempat itu, lalu kembali ke keadaan atau tempat semula. Para pakar bahasa Arab, membagi makna fitrah ke dalam tiga bagian, yaitu: asal kejadian, agama yang benar, dan kesucian.
Asal kejadian
Ketika mula pertama manusia diciptakan, ia telah mengikat perjanjian primordial dengan Allah SWT, yaitu ikrar pengakuan untuk bertauhid dan mengabdi kepadaNya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Hal ini diungkapkan al-Qur’an di kala manusia berada di alam arwah, Allah SWT bertanya:
…أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ …
“… Bukankah Aku Tuhan kalian? Manusia saat itu menjawab, benar Engkau adalah Tuhan kami…” (QS al-A’raf/7:172).
Redaksi kalimat dalam ayat tersebut diawali dengan “istifham inkariy,” yakni pertanyaan yang bersifat negatif أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ (bukankah Aku Tuhan kalian?). Sedangkan jawabannya menggunakan kata بَلَىٰ yang berarti membenarkan pertanyaan dalam bentuk positif, walaupun redaksinya berbentuk negasi. Dengan demikian, jawaban ini mengandung arti, “benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami.” Ibn ‘Abbas mengatakan, seandainya kata بَلَىٰ pada ayat itu ditukar dengan نعم (na’am), akan mengakibatkan kekufuran, sebab kata na’am digunakan sebagai jawaban untuk membenarkan pertanyaan, baik yang berbentuk positif maupun negatif. Bila pertanyaan “bukankah Aku Tuhan kalian” dijawab dengan kata na’am, berarti membenarkan redaksi yang bersifat negatif, sehingga jawaban itu mengandung arti: “benar, Engkau bukan Tuhan kami.”
Berdasarkan penjelasan ini, ‘idul fitri dapat dipahami “kembali kepada kemurniaan akidah dan kesempurnaan iman.” Selama sebelas bulan, mungkin akidah yang lurus tercemari dan tereduksi dengan noda-noda syirik. Ramadhan menjadi momentum untuk memurnikan akidah dan menyempurnakan iman. Sejalan dengan do’a yang senantiasa dipanjatkan seusai shalat tarawih “Allahummaj’alna bi al-imani kamilin (Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya).
Agama yang benar
Dalam al-Qur’an dinyatakan, agama yang diridhai Allah SWT adalah Islam. Secara tegas diungkapkan al-Qur’an:
إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam… “ (QS Ali ‘Imran/3:19).
Dari konteks ini, ‘idul fitri mengandung arti “kembali kepada kehidupan yang Islami, yakni menjalankan ajaran-ajaran Islam secara kaffah (total) di dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti, menyangkut perihal beragama tidak dibenarkan seorang Muslim mengerjakan sebagian perintah yang telah ditetapkan syari’at, lalu meninggalkan sebagian perintah lainnya. Begitu pula meninggalkan sebagian larangan, namun mengerjakan larangan yang lainnya. Contoh konkret, ia melaksanakan shalat, namun enggan berzakat. Atau rajin berzakat, tetapi tidak melaksanakan shalat. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan, ada orang yang tidak shalat, akan tetapi rajin menunaikan puasa. Al-Qur’an mengingatkan kekeliruan cara beragama seperti itu, dan dinyatakan dalam QS al-Baqarah/2:208:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”
Kaffah menghendaki penyerahan total yang seimbang antara jiwa dan raga, pribadi dan organisasi, karir dan rumah tangga, pendidikan dan keuangan. Bukanlah kaffah, jika bertahajud di sepertiga malam terakhir memohon kepada Allah, namun keesokan harinya di saat berbisnis menggantungkan diri pada paranormal. Tidaklah dikatakan kaffah ketika beribadah merujuk al-Qur’an dan Sunnah, namun giliran berekonomi menggunakan cara ribawi.
Muslim yang kaffah diilustrasikan QS Ibrahim/14:24-25 laksana pohon thayyibah yang memiliki tiga karakteristik. Pertama, Ashluha Tsabitun (akarnya kokoh menghunjam di dalam tanah). Ini menggambarkan, seorang Muslim hendaklah memiliki akidah yang kokoh, seperti kokohnya akar yang terhunjam di dalam tanah. Rasulullah saw dan para sahabat merupakan teladan yang sangat kokoh akidahnya. Pada waktu paman Rasul, Abu Thalib menyarankan untuk menghentikan aktivitas dakwah, agar tidak ada lagi intimidasi, ancaman, serta berbagai tindak kekerasan dari kalangan orang-orang musyrikin Mekkah, Rasulullah saw menjawab dengan tegas:
يا عم، والله لو وضعواالشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذاالأمر حتى يظهرالله أو أهلك فيه ما تركته
“Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan (dakwah) ini, sungguh aku tidak akan meninggalkannya, sehingga Allah menampakkan kemenangan atau aku hancur karenanya.”
Mendengar jawaban Rasulullah saw, Abu Thalib tertegun, dan akhirnya berkata:
إذهب يابني أخي فقل أحببت فوالله لا أسلمك لشيئ تكرهه أبدا
“Pergilah wahai anakku, katakan sekehendakmu, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu bagaimana pun juga.”
Kekokohan akidah Rasulullah saw dalam mempertahankan kebenaran meluluhkan hati Abu Thalib yang akhirnya berbalik simpatik. Sejak itu, Abu Thalib menjadi pelindung Rasulullah saw hingga menemui ajalnya. Kisah lain yang inspiratif adalah keteladanan Sa’ad bin Abi Waqas. Ketika ia masuk Islam, ibunya marah dan mengancam akan mogok makan, seraya berkata: “wahai Sa’ad, jika ibu mati, maka pasti masyarakat di sekitar ini menuduh serta mencemooh, bahwa engkau adalah pembunuh ibunya sendiri.” Di saat Sa’ad menyaksikan ibunya dalam kondisi kritis karena melakukan mogok makan, lalu Sa’ad berkata: “andaikan ibu memiliki seratus nyawa, kemudian keluar satu persatu, sungguh aku tidak akan meninggalkan Islam sebagai agama yang telah aku yakini kebenarannya.” Sekarang terserah ibu, jika mau makan, maka makanlah, dan jika tetap bersikukuh pada sikap semula, maka lakukan apa yang ibu suka. Pernyataan dan sikap tegas dari Sa’ad bin Abi Waqas menyebabkan ibunya tercengang dan sadar, aksi mogok makan pun dihentikan.
Kedua, Far’uha fi al-sama’ (batang dan rantingnya tinggi menjulang ke langit). Perumpamaan ini menggambarkan aktivitas seorang Muslim yang senantiasa menjalin komunikasi secara vertikal dengan Allah SWT. Ia selalu mengaktualisasikan tindakannya sebagai pengabdian kepada Khaliq, sehingga nilai akhir yang dilakukannya melahirkan ibadah. Hal ini sejalan dengan penegasan al-Qur’an:
وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ
“Tidaklah semata-mata Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu” (QS al-Dzariyat/51:56).
Oleh karena itu, apapun karya dan prestasi yang dihasilkan manusia, bila tidak melahirkan nilai ibadah, maka tidaklah bermakna dan sia-sia. Berkenaan dengan ini, sahabat Ali karamallahu wajhah menyatakan:
من كانت همته لبطنه فقيمته ما يخرج منه
“Barangsiapa yang orientasi hidupnya, hanya untuk kepentingan perut semata, maka nilainya sama dengan apa yang keluar dari perutnya.”
Minimal 17 kali umat Islam berikrar menyatakan kepatuhan dan ketundukannya semata-mata kepada Allah SWT:
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ
“Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan” (QS al-Fatihah/1:5).
Ketiga, Tu’ti ukulaha kulla hinin bi idzni Rabbiha (memberikan buahnya seizin Tuhannya). Ini merupakan gambaran, seorang Muslim harus memiliki akhlak mulia yang memberikan manfaat untuk sesamanya. Rasulullah saw bersabda:
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
“Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya…” (Riwayat Tirmidzi).
Akhlak adalah buah dari akidah (keimanan) dan ibadah yang terjelma dalam realitas kehidupan. Shalat, puasa, zakat, dan haji mempunyai kaitan langsung dengan akhlak. Seseorang yang mendirikan shalat, tentu tidak akan mengerjakan segala perbuatan yang keji dan mungkar (QS al-‘Ankabut/29:45), sebab apalah arti shalatnya jika ia tetap mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Seseorang yang benar-benar berpuasa, di samping menahan keinginannya untuk makan dan minum, tentu juga akan menahan dirinya dari segala kata-kata yang kotor dan tercela (Hadis Riwayat Ibnu Khuzaimah). Begitu pula dengan zakat dan haji, Allah SWT mengaitkan hikmahnya dengan aspek akhlak (QS al-Taubah/9:103; QS al-Baqarah/2:197). Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Karena itu, Rasulullah saw menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam.
Kesucian
Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, yakni terbebas dari dosa dan kesalahan. Rasulullah saw bersabda:
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Disebabkan kedua orangtuanyalah ia menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (Riwayat Bukhari).
Ungkapan hadis tersebut menunjukkan, bahwa kecenderungan dasar manusia adalah monoteisme (menyembah Tuhan yang satu). Namun perjalanan hidupnya seringkali menorehkan noda-noda kemaksiatan yang mengotori lembaran suci yang seharusnya dijaga dan dipelihara kemurniannya. Jalaluddin Rumi melukiskan perjalanan hidup manusia selama sebelas bulan laksana menanam semak berduri. Semak itu sudah banyak melukai orang lain, juga dirinya sendiri. Dalam suasana ‘idul fitri, cabutlah semak-semak berduri secara jantan, seperti sahabat Ali menghancurkan benteng “Khaibar.” Kini saatnya mengganti semak berduri yang seringkali membawa bencana dengan rumpun mawar yang menyejukkan serta membawa kedamaian.
Dosa mengakibatkan manusia menjauh dari Allah SWT. Kisah Nabi Adam dan Hawa yang terusir dari surga karena melakukan pelanggaran, menunjukkan bahwa perbuatan dosa menjadikan seorang hamba jauh dengan Tuhannya. Padahal awalnya, posisi Nabi Adam dan istrinya begitu dekat dengan Allah, sehingga seluruh fasilitas di surga disiapkan untuk mereka berdua (QS al-Baqarah/2:35). Agar kembali dekat pada posisi semula, manusia harus menyadari kesalahan yang disertai upaya maksimal memperbaikinya. Inilah yang disebut “taubatan nasuha” (kembali ke jalan Allah dengan sungguh-sungguh). Betapapun bergelimang dosa, Allah SWT akan menerima hambaNya yang bertobat, karena sesungguhnya Allah selalu merindukan hamba-hambaNya yang kembali ke jalan yang benar (QS al-Isra/17:8).
Manusia lahir dalam fitrah, berarti manusia hidup dalam kesucian. Allah SWT menyediakan bulan Ramadhan sebagai upaya menyucikan diri, yaitu membuat diri kembali suci, sehingga bulan Ramadhan bukan saja bulan suci, tetapi bulan penyucian. Implikasi yang diharapkan, 1 Syawal menjadi momentum seakan-akan manusia dilahirkan kembali seperti bayi yang tidak memiliki dosa.
Dengan selesainya melaksakankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, bukan berarti selesai pula mengerjakan amal-amal kebajikan. Pepatah Arab mengatakan, “kun Rabbaniyan, wa la takun Ramadhaniyan” (jadilah orang yang dapat meneladani sifat-sifat Ketuhanan untuk sepanjang zaman, dan janganlah hanya menjadi orang yang meramaikan Ramadhan untuk satu bulan).
Ibadah tidak hanya berhenti pada tataran teologis melalui kesalehan individual berupa shalat, puasa, zakat, haji, dan tadarus al-Qur’an. Tetapi semua itu harus menjelma dalam kesalehan sosial berwujud amal-amal kebajikan terhadap sesama manusia. Dalam ajaran Islam, manusia tidak dapat dilepaskan dari dua jalur komunikasi, yaitu vertikal dengan Allah SWT (hablun min Allah), dan khorizontal dengan sesama umat manusia (hablun min al-nas). Inilah yang menjadi output pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan, yakni mencapai derajat termulia sebagai muttaqin (orang-orang yang bertakwa). ‘Idul fitri adalah puncak idealitas manusia.
Wallahu A’lam