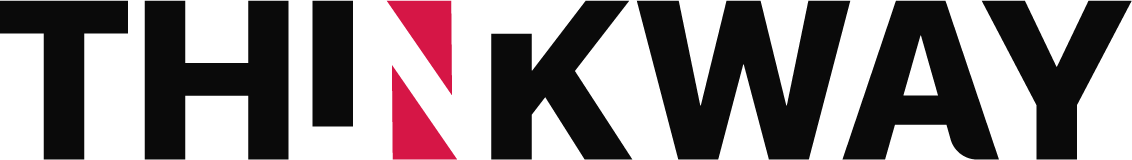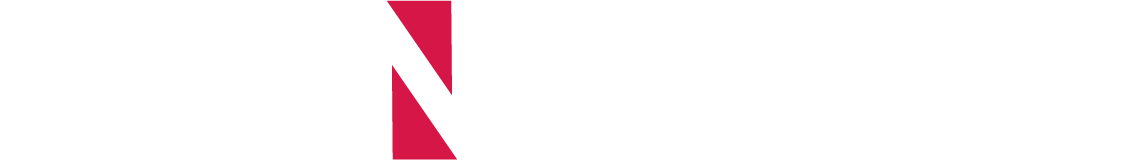“Malem Minggu aye pergi ke bioskop..
Bergandengan ame pacar nonton koboi..”
THINKWAY.ID – Ada dimensi usia yang tergambar dalam lirik lagu Nonton Bioskop karya Benyamin Sueb. Yang bikin bioskop jadi salah satu destinasi muda-mudi buat ngabisin waktu. Mungkin itulah mengapa wajah bioskop nggak mudah keriput dimakan usia. Nggak kaya pasar malam, mall, dan restoran yang makin tergantikan oleh perkembangan zaman.
Masih ingat sama Alexander Thian yang nyewa satu bioskop cuma buat nonton Spiderman: No Way Home? Terlepas dari kontroversi yang mengiringi dan karena alasan pandemi, nyatanya sensasi nonton di bioskop emang nggak bisa tergantikan begitu aja. Meskipun ada home theater dan TV dengan layar besar sekalipun vibes-nya bakalan beda banget. Itulah mengapa layanan streaming nggak bisa memudarkan daya tarik bioskop.
Cikal Bakal Bioskop di Indonesia
Istilah bioskop diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, bios yang artinya hidup dan skopeein yang berarti melihat. Awalnya, ada orang Italia bernama Athanasius Kircher yang berhasil memanipulasi gambar bergerak di tahun 1640. Ia menyebut temuannya itu dengan nama magia catotrica, yang berarti lentera ajaib. Setelahnya di tahun 1853, Simon Ritter von Stampfer dari Austria membuat sebuah stroboscope. Sebuah gambar tembus pandang yang bisa dipantulkan cahaya.
Dua penemuan itu makin berkembang di tahun-tahun berikutnya, sampai akhirnya pada 1 November 1895 ada sebuah pertunjukan gambar bergerak yang diputar di Berlin, dan Atlanta Amerika Serikat di tahun yang sama. Tapi peristiwa yang mengawali lahirnya bioskop tetap merujuk pada pertunjukkan Paris, 28 Desember 1895. Ketika Lumiere bersaudara menggelar pertunjukan gambar bergerak di sebuah kedai kopi, yang mana setiap penontonnya diwajibkan untuk membayar.
Ternyata enggak butuh waktu lama, demam bioskop langsung merayap sampai Hindia-Belanda. Dafna Ruppin dalam karyanya The Komedi Bioscoop: The Emergence of Movie-Going in Colonial Indonesia, 1896-1914, nulis kalo pada tanggal 11 Oktober 1896, surat kabar Javabode masang iklan tentang pertunjukan sinema di Schouwburg (sekarang Gedung Kesenian Jakarta). Harga tiketnya sebesar f1(1 Gulden), dengan jadwal pemutaran di jam 17.30 dan jam 18.30.
Tapi buat nyebutin bioskop pertama di Indonesia biasanya orang-orang merujuk pada 5 Desember 1900. Ketika seorang pengusaha Belanda bernama Louis Talbot mendirikan bioskop di rumahnya. Sebagai penyelenggara, De Nederlandsch Bioscope Maatschaij masang harga f2 buat tiket kelas 1, f1 buat tiket kelas 2, dan 50 sen buat tiket kelas 3. Pada 28 Maret 1903, tempat itu disulap jadi The Roijal Bioscope yang jadi awal pendirian gedung bioskop di Indonesia.
Waktu itu film yang diputer masih sederhana banget, masih hitam putih, tanpa dialog, cuma musik pengiring doang. Judulnya “Sri Baginda Maharatu Belanda bersama Pangeran Hertog Hendrick Memasuki Ibu Kota Belanda, Den Haag”. Sebenernya pengusaha Belanda lain yang bernama Schwarz juga pernah bikin bioskop di daerah yang sekarang disebut Kebon Jahe, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Cuma nasibnya tragis, karena bioskopnya habis dilahap api.
Setelah Jakarta, kota Bandung juga akhirnya punya bioskop bernama Bioskop Helios di Jalan Braga yang berdiri tahun 1905. Pada 31 Desember 1926, di kota ini juga film pertama karya sineas lokal yang berjudul Loetoeng Kasaroeng diputar di layar lebar. Film itu diproduksi oleh NV Java Film Company. Sebuah perusahaan perfilman yang dibangun oleh L Heuveldorp dan G. Krugers. L. Heuveldorp adalah warga negara Belanda yang kenyang pengalaman dalam dunia perfilman Amerika. Sementara G. Krugers adalah seorang Indo-Belanda yang bertindak sebagai sebagai juru kamera.
Pertumbuhan bioskop makin menjamur di tahun-tahun setelahnya, antusiasme ini berbuah badan Nederlandsch Indiesche Bioscoopbond (Persatuan Bioskop Hindia Belanda) pada 13 September 1936. Setelah Indonesia merdeka, terhitung ada sekitar 300 gedung bioskop yang udah eksis. Termasuk Bioskop Metropole yang diresmikan Rahmi Rachim Hatta, Haji Agus Salim, dan Sultan Hamengkubuwono IX di tahun 1951. Bioskop yang berkapasitas 1.700 kursi itu adalah bioskop terbesar di masanya, dan masih beroperasi sampai sekarang.
Tapi di masa kependudukan Jepang, jumlah itu menyusut hingga 52 gedung aja di enam kota besar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Gedung-gedung itu banyak yang beralih fungsi jadi gudang bahan pokok, selain karena menurunnya minat menonton film akibat terlalu banyak diisi dengan propaganda Jepang.
Demam drive-in-theatre juga melanda Indonesia di masa itu. Sebuah cara menikmati film di dalam mobil, dengan layar bioskop yang super besar. Ide ini pertama kali digelar oleh pihak The Airdome Theater di daerah Las Cruces, Meksiko, Amerika Serikat pada 11 Juni 1914. Film pertama yang diputar ialah For Napoleon and France garapan sutradara asal Italia Enrico Guazzoni. Fenomena drive-in-theatre kian populer di Amerika, sampai-sampai seorang Richard M. Hollingshead, Jr mematenkan konsep itu di Chamden, New Jersey pada 6 Juli 1933.
Sementara di Indonesia, drive-in-theatre pertama kali digagas oleh pengusaha Ciputra di tahun 1970-an. Ia menawarkan ide ini setelah pengalamannya berkunjung ke New York, di masa itu pertumbuhan mobil juga semakin meningkat. Pada 1 Mei 1970, Kompas menyebutkan bahwa bioskop itu adalah drive-in-theatre terbesar di Asia Tenggara. Sayang drive-in-theatre itu tidak bertahan lama, karena pada 1990 Ciputra mengubahnya menjadi pusat belanda busana denim.
Bioskop dan Kelas Sosial
Pada awalnya bioskop adalah hiburan untuk kalangan menengah atas, karena harga tiket kelas 3 yang seharga setengah Gulden, senilai dengan 10 kg beras di masa itu. Alwi Shahab dalam karyanya Saudagar Baghdad dari Betawi, menjelaskan tentang pembagian kelas di bioskop sesuai tempat duduknya. Ada kelas balcon, loge, stelles, dan kelas 1, di beberapa tempat dibagi menjadi tiga kelas, 1, 2, dan 3. Prinsipnya semakin jauh dari layar harganya semakin mahal.
Menurut Fandy Hutari, kelas 3 diperuntukkan khusus untuk orang-orang Slam (Betawi Muslim) dan Jawa. Pembagian ini sangat diskrimanatif, karena pihak bioskop memastikan orang Eropa dan Tionghoa enggak masuk ke barisan kelas 3. Itulah kenapa harga di kelas 3 hanya f0,25, sangat murah dibanding dua kelas lainnya (f1 dan f0,50).
Perkembangan yang pesat bikin bioskop makin ngetren, bisnis ini akhirnya merambah pasar kelas bawah. Bukan di gedung mewah, tapi di lapangan terbuka, seperti layar tancep. Jadi kalo gerimis penonton buru-buru bubar. Dari sanalah istilah misbar muncul (gerimis bubar). Bioskop rakyat juga biasa disematkan berdasarkan letak teritori. Biasanya terletak di dekat pemukiman rakyat kelas bawah, di antaranya ada bioskop Ratna dan bioskop Gembira yang terletak di kedua ujung Jalan Kawi Jakarta Selatan.
Kelas kambing adalah sebutan khusus untuk sebagian fasilitas publik yang berkualitas rendah. Selain di sektor transportasi, deretan kelas 3 dan 4 di bioskop juga disebut sebagai kelas kambing. Soekarno pernah jadi bagian penonton di kelas ini, biasanya ditempatkan di depan layar, bahkan ada juga yang di belakang layar. Mereka dianggap sering berulah, dan terkenal berisik ketika nonton.
Beruntung di masa sekarang, kita bebas memilih tempat duduk dengan fasilitas yang nyaman. Sehingga personal experience-nya jadi lebih berkesan, dengan harga yang relatif terjangkau. Setelah 122 tahun eksis, bioskop tetap jadi tujuan muda-mudi melepas penat atau sekadar PDKT dengan pasangan. Wajah bioskop enggak berkerut meskipun zaman sedang kusut.
Terbukti di Australia, Amerika, dan Korea Selatan drive-in-theatre jadi alternatif tujuan buat yang pengen nonton tapi aman di masa pandemi. Park Dong Ju, selaku pengelola drive-in-cinema in Seoul mengaku mengalami peningkatan omzet sebanyak 10-10 persen di masa pandemi. Sepertinya bioskop memang dibuat selalu relevan dengan zaman. Jadi apakah reff lagu Nonton Bioskop masih terasa mewah kalo bioskop jadi makin mudah diakses?